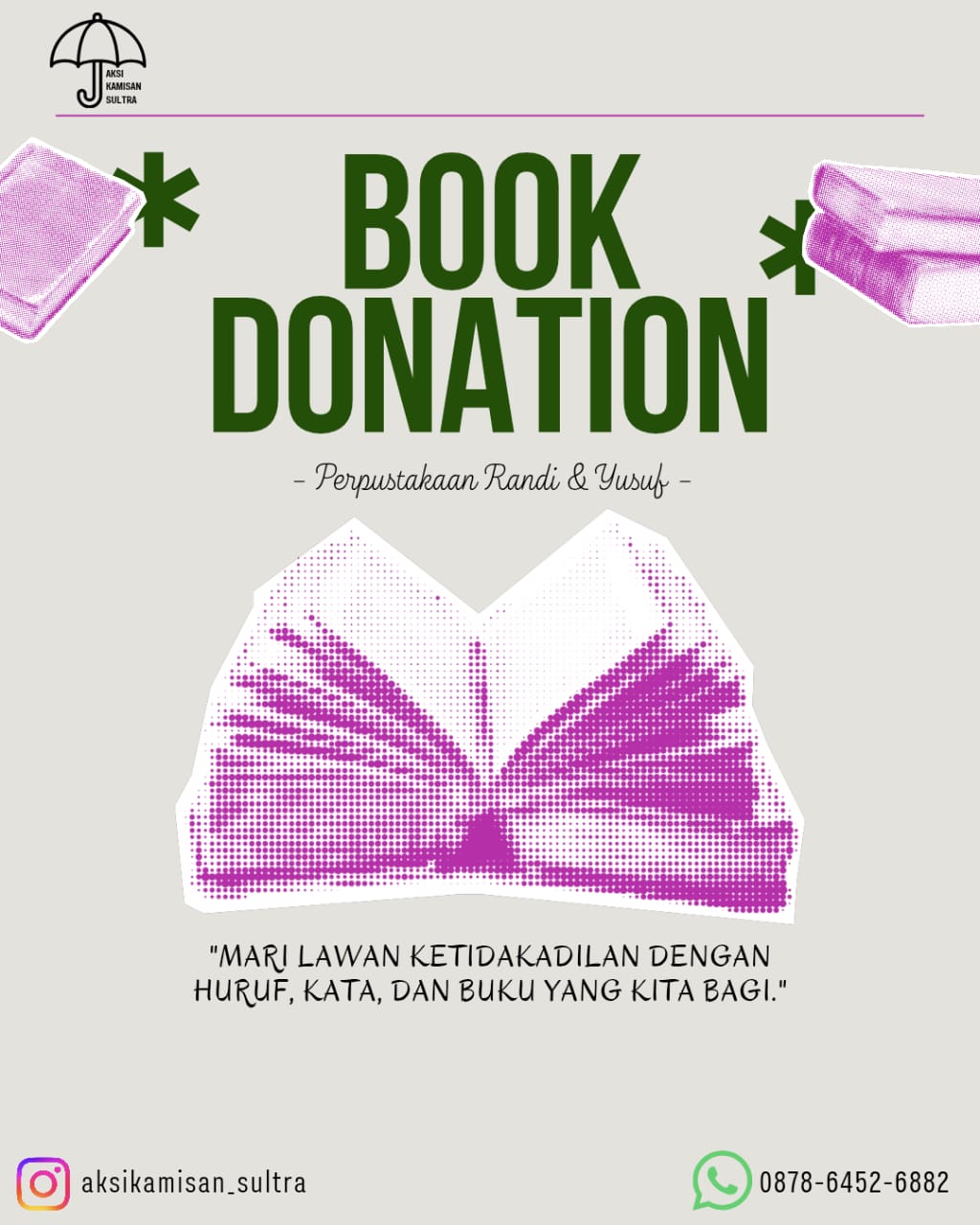Ketika nama Marsinah disebut lagi di Istana Kepresidenan pada 10 November 2025, pagi terasa seperti datang terlambat. Di panggung negara, gelar Pahlawan Nasional disematkan kepada seorang buruh perempuan yang 32 tahun sebelumnya ditemukan tak bernyawa di hutan kecil Dusun Jegong, Wilangan. Upacara berlangsung rapi, resmi, di ruang yang selama ini tak pernah ia tapaki. Keluarganya duduk di baris tamu kehormatan, menyaksikan sejarah memberi ruang baru bagi seorang perempuan yang dulu suaranya lebih sering dipotong daripada didengar.
Keputusan itu termaktub dalam Keppres No. 116/TK Tahun 2025. Bagi banyak orang, penetapan ini bukan sekadar penghargaan, tetapi penanda bahwa kisah yang dulu hendak dikubur diam-diam kini berdiri kembali, lengkap dengan luka dan pertanyaannya.
Marsinah bukan aktivis yang lahir dari panggung ideologi besar. Ia bukan mahasiswa, bukan elit gerakan. Ia hanya pekerja pabrik arloji, perempuan buruh di PT CPS Porong, yang setiap harinya berhadapan dengan mesin, jam, dan batas waktu. Namun dari tubuh kecil itulah lahir suara yang mengguncang struktur tempatnya bekerja dan berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar dari yang pernah ia kira.
Buruh Perempuan yang Menolak Diam
Awal Mei 1993. Suhu panas di Porong seakan menempel di kulit para buruh yang berkumpul di halaman pabrik. Mereka menuntut kenaikan upah, sebuah tuntutan sederhana dalam kehidupan yang batasnya direntang oleh kebutuhan makan sehari-hari.
Pada hari pertama aksi mogok Yudo Prakoso, koordinator aksi ditangkap dan dibawa ke Koramil. Di ruang interogasi, ia dituduh melakukan protes dengan cara yang “mirip aksi Partai Komunis Indonesia (PKI).” Ketika Yudo tak kembali, suara di barisan buruh sempat terhenti. Namun tak lama kemudian, perempuan itu maju ke depan. Marsinah mengambil alih komando.
Sejak hari itu, para buruh mengenal dua wajah kekuasaan: pabrik yang membatasi, dan aparat yang mengawasi. Keduanya berkelindan dalam aturan era Orde Baru yang memberi peran luas bagi militer dalam urusan buruh. “Di bawah rezim militeristik Orde Baru, Soeharto memastikan adanya payung hukum untuk mengawasi dan mengatur protes buruh,” salah satunya melalui SK Bakorstanas No. 02/Satnas/XII/1990 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 342/Men/1986.
Aturan itu menempatkan militer sebagai penengah, sebuah posisi yang dalam praktiknya sering menjelma menjadi pengawas penuh atas gerak buruh.
Pertemuan yang Tak Pernah Selesai
Aksi mogok memasuki hari kedua. Negosiasi dilakukan: 15 perwakilan buruh, termasuk Marsinah, bertemu dengan pihak perusahaan, Departemen Tenaga Kerja, polisi, aparat kecamatan, dan Koramil. Hampir semua tuntutan dikabulkan, kecuali satu: pembubaran SPSI tingkat pabrik. SPSI saat itu adalah satu-satunya serikat buruh yang diakui negara, dan keberadaannya tidak boleh diganggu.
Di hari yang sama, Yudo kembali dipanggil ke Kodim 0816 Sidoarjo. Ia diminta mencatat nama-nama buruh yang terlibat dalam penyusunan tuntutan. Catatan itu kelak menjadi daftar yang membuat banyak buruh tidak pernah merasa aman lagi.
Marsinah tidak hadir dalam pertemuan itu, tetapi namanya tercantum di daftar. Tiga hari kemudian, ia hilang.
Pada 8 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan di tepi hutan kecil, dalam keadaan rusak oleh luka-luka yang tak mungkin datang dari kecelakaan biasa. Dokter forensik Abdul Mun’im Idries, dalam hasil visum kedua, mencatat temuan yang kemudian banyak dikutip:
“Terdapat tulang kemaluan kiri yang patah berkeping-kepin, tulang usus kanan rusak hingga terpisah, tulang selangkangan kanan patah.”
Ada pula luka selebar tiga sentimeter di bagian luar alat kelamin, yang menurut sang dokter “tidak setara dengan barang bukti yang jauh lebih besar” yang sebelumnya disebut penyidik.
“Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak?” Tambah Mun’im.
Itu berarti, menurutnya, pelaku merupakan seorang yang memiliki akses terhadap senjata api di masa Orde Baru.
Sidang yang Berliku dan Skenario yang Retak
Kasus Marsinah kemudian bergerak ke pengadilan. Namun prosesnya sarat kejanggalan.
Majalah Tempo mencatat bahwa Yudi Santoso, pemilik pabrik PT CPS, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menuduh pembunuhan itu dilakukan karena “Marsinah terlalu vokal melawan perusahaan.”
Namun di persidangan, Yudi membantah keras. Ia mengaku dipaksa dan disiksa untuk mengaku sebagai dalang pembunuhan.
Dalam arsip yang sama, seorang perwira militer bernama Kapten Kusaeri disebut sebagai sosok yang menggagas narasi bahwa kematian Marsinah adalah “shock therapy” agar Marsinah jera. Ia juga mengatakan kematian itu “tidak sengaja”.
Tiga orang akhirnya divonis, Suwono dan Suprapto masing- masing 12 tahun dan Yudi Santoso 20 tahun.
Namun semuanya dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Setelah itu, kasus kembali sunyi.
Tubuh Perempuan dalam Pertarungan Kekuasaan
Kisah Marsinah memunculkan satu garis yang sulit dihapus: bagaimana tubuh seorang buruh perempuan berada dalam persilangan kekuasaan negara, perusahaan, dan aparat militer. Konflik upah yang ia perjuangkan bukan hanya soal angka di kertas gaji, tetapi juga tentang batas-batas siapa yang boleh bersuara dan siapa yang tidak.
Di masa itu, buruh perempuan sering dianggap paling mudah diredam. Posisi mereka di pabrik adalah posisi yang secara sosial dipandang “lemah,” sehingga ketika Marsinah muncul sebagai pemimpin aksi, ia bukan hanya melampaui peran gender, tetapi juga menembus struktur kontrol yang dibangun Orde Baru.
Dalam narasi aparat, aksi Marsinah bahkan dihubungkan dengan cara-cara “PKI”, sebuah stigma yang pada masa itu menjadi alat pembungkam paling efektif. Ketika tuduhan seperti itu muncul, pintu keselamatan bagi seorang buruh perempuan akan semakin mengecil.
Kisah ini bukan tentang seorang aktivis besar, tetapi tentang seorang pekerja yang hidup dalam dunia di mana suara buruh perempuan ditempatkan paling bawah dalam hierarki sosial dan paling rentan ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Pahlawan di Ruang yang Tak Ia Datangi
Tiga puluh dua tahun setelah tubuh itu ditemukan, gelar Pahlawan Nasional akhirnya diberikan. Presiden Prabowo Subianto bahkan pernah mengatakan dalam aksi hari buruh lalu, “Saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional.”
Upacara penetapan berlangsung tanpa ketegangan, tanpa penghilangan, tanpa interogasi. Namun ruang itu tetap membawa bayangan masa lalu: ruang yang sama yang dulu tidak menyediakan perlindungan ketika hidup Marsinah meruncing menuju kematiannya.
Kini, nama Marsinah disebut di podium negara sebuah panggung yang dulu berada sangat jauh dari jangkauan seorang buruh perempuan pabrik arloji.
Penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional tidak serta-merta menyelesaikan perjalanannya. Ia bukan sekadar nama yang diukir pada plakat penghargaan; ia adalah ingatan kolektif tentang bagaimana suara buruh perempuan pernah bersinggungan langsung dengan aparatur kekuasaan yang memiliki hak untuk menentukan hidup dan matinya seseorang.
Dan selama kisah itu tetap diceritakan, Marsinah tidak pernah benar-benar hilang.