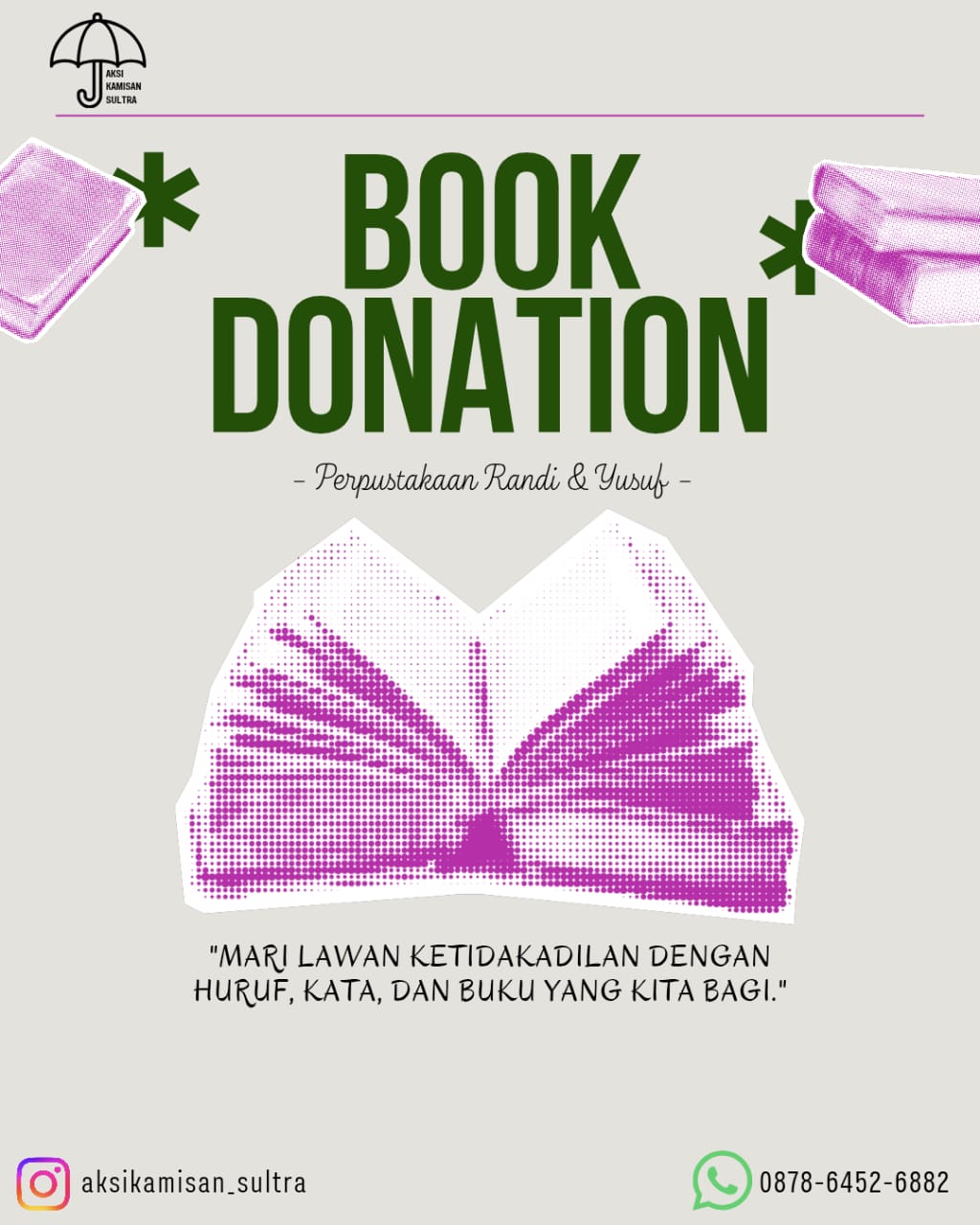Di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, berladang bukan sekadar aktivitas bercocok tanam, tetapi bagian dari cara hidup masyarakat adat yang disebut Monta’u — sistem berladang pindah yang sarat makna spiritual dan ekologis. Tradisi turun-temurun ini mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam.
Bentara Timur – Di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, berladang bukan sekadar cara bertanam. Bagi masyarakatnya, kegiatan ini adalah cara menjaga hubungan dengan alam, mempertahankan identitas, dan merawat kearifan yang diwariskan lintas generasi.
Mereka menyebut tradisi itu Monta’u, sistem berladang pindah yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun.
Di balik kesederhanaannya, Monta’u menyimpan filosofi yang dalam. Tanah bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri.
Ahiruddin, pria paruh baya warga Desa Noko, mengenang masa ketika hampir seluruh penduduk Wawonii masih membuka ladang dengan cara tradisional. Mereka menebas semak, menebang pohon, lalu membakar sisa vegetasi sebelum mulai menanam.
“Dulu semua dilakukan berpindah, setelah tanah mulai keras baru buka lahan baru,” ujarnya.
Proses ini dikenal sebagai tebang, tebas, bakar, mirip dengan sistem perladangan tradisional di beberapa tempat di Indonesia
Tapi di Wawonii, pembakaran dilakukan dengan hati-hati. Warga mengenal istilah hari api, yakni waktu khusus untuk membakar lahan secara terkendali. Ada ritual kecil agar api tak meluas, tak membakar hutan, dan tak menjalar ke tanah tetangga.
Secara ilmiah, praktik ini punya dasar ekologis. Pembakaran dalam kadar tertentu bisa menyuburkan tanah. Abu dan arang bekas pembakaran mengandung fosfor , unsur penting bagi pertumbuhan akar dan fotosintesis. Sebuah penelitian berjudul “Biomass ashes and their phosphorus fertilizing effect on different crops” (2010) menyebutkan bahwa abu sisa pembakaran batang dan daun dapat menjadi sumber nutrisi alami bagi tanaman.
Berladang, Menjaga Alam dan Keragaman Pangan
Kini, tradisi Monta’u mulai jarang ditemukan. Lahan baru sulit dibuka, dan hanya beberapa desa seperti Dimba, Ladianta, Noko, dan Mawa yang masih mempertahankannya.
Di sana, para peladang tetap menanam padi ladang. Pae, sebutan padi dalam bahasa Wawonii, bersama tanaman lain seperti labu (supere), mentimun, kopi gandu (hoinu), daun melinjo (lewe huka), dan jamur (olepe), terong hutan (kotiwu),
“Berladang bukan hanya soal menanam padi dan sayuran, ini juga tentang menghormati tanah, menjaga keseimbangan, dan hidup berdampingan dengan alam,” kata pria yang keseharianya juga bekerja sebagai guru.
Dalam Kabanti, Jurnal Kerabat Antropologi, peneliti Hasniati menyebut bahwa Monta’u di Desa Mawa adalah bentuk perlindungan terhadap alam dan ekologi. Sistem ini bukan hanya bertujuan ekonomi, tapi juga menjaga keanekaragaman hayati.
Pae yang Dihormati, Tanah yang Dijaga
Bagi orang-orang Wawonii, Pae dipersonifikasikan sebagai entitas yang berjiwa. Tokoh masyarakat, Muhammad Nasrun (58), menjelaskan bahwa penghormatan terhadap Pae melahirkan banyak pantangan. Salah satunya, dilarang membawa api ke ladang saat masa padi menunggu panen, pamali yang dipercaya bisa mendatangkan bala atau malapetaka bagi hasil panen.
Bagi warga Wawonii proses berladang sendiri melewati lebih dari sepuluh tahapan, seluruhnya dilakukan dengan alat sederhana, kapak dan parang
Mulai dari Molelei atau survei lahan, Modaha (menebang pohon besar), Sumongko (membakar terbatas), hingga Montasu (menugal), yakni menanam dengan tongkat kayu runcing untuk melubangi tanah dan menebar benih padi satu per satu.
Ketika panen tiba, proses Mosowi dilakukan dengan ani-ani, alat kecil dari bambu yang diselipkan di jari untuk memotong bulir padi satu per satu. Menggunakan sabit atau mesin perontok dianggap tabu karena bisa “menyakiti” Pae.
Setelah panen, padi dikeringkan di atas tungku (pea) dan ditumbuk di lesung atau istilahnya Membeu, hingga menjadi beras yang siap disantap bersama sayur dan hasil ladang lain.
Ladang yang Menyempit, Tradisi yang Tergerus
Namun dua dekade terakhir, Monta’u menghadapi tantangan besar. Lahan yang dulu luas kini makin sempit. Banyak tanah yang dulu menjadi ladang kini beralih fungsi untuk pembangunan dan ironisnya untuk pertambangan.
“Sekarang lahan sudah susah. Anak-anak muda banyak yang tidak lagi berladang. Mereka cari kerja di tambang atau pergi kota. Mereka bekerja di sana, di toko, di bank, macam-macam,” ujar Nasrun.
Program intensifikasi pertanian juga membuat masyarakat beralih ke sawah dan komoditas pasar. Akibatnya, jumlah peladang menurun, dan akses terhadap pangan lokal ikut berkurang.
Padahal, ladang-ladang tradisional dulu menjadi sumber pangan utama tempat tumbuh berbagai tanaman lokal, jamur, sayur liar, hingga obat-obatan. Kini, banyak dari itu yang mulai hilang bersama berkurangnya ruang hidup warga.
Bagi sebagian warga Wawonii, mempertahankan Monta’u berarti menjaga hubungan dengan leluhur dan alam. Tradisi ini bukan sekadar metode bertani, tetapi cara memahami dunia bahwa tanah harus dijaga, bukan dieksploitasi.
“Kalau tanah rusak, manusia ikut rusak. Berladang itu cara kami berbicara dengan alam, bukan melawannya,” kata Ahiruddin.
Di tengah tekanan modernisasi dan industrialisasi, Monta’u tetap hidup dalam ingatan, ritual, dan cerita. Tradisi yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan waktu.
Penulis : Rosniawanti